Permasalahan Pendidikan di Indonesia
Memasuki 2026, slogan Indonesia Emas 2045 terasa sudah jarang digaungkan saat ini, tidak masif lagi gembar-gembornya seperti beberapa tahun yang lalu. Dengan jangka waktu 19 tahun lagi, nampaknya harapan masa keemasan Indonesia tersebut mulai dilupakan atau mungkin mulai ada kepasrahan karena dirasakan semakin sulit diraih?
Dalam kacamata saya, mewujudkan zaman keemasan sebuah negara dengan segala kompleksitasnya dalam jangka waktu dua dekade kurang sedikit itu memang terasa sangat over confidence. Apalagi kalau melihat realitas di lapangan, saya makin sulit untuk optimis. Setidaknya hal ini bisa dikonfirmasi apabila kita menilik pada salah satu aspek dari sekian banyak hal yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat, saya bahas di sini aspek pendidikan.
1. Masalah Klasik : Kurikulum Pendidikan
Pada era pemerintahan sebelumnya, dunia pendidikan Indonesia coba meniru negara Nordik yang memberikan banyak kebebasan pada siswa. Pendekatannya adalah berusaha menghargai apapun level kemampuan siswa, tidak membeda-bedakan kemampuan akademis, menghindari pemberian beban terlalu banyak pada siswa. Bertemulah kita dengan "merdeka belajar", yang saking merdekanya sampai dikeluhkan adanya siswa SMP yang belum lancar membaca.
Sebenarnya fenomena tersebut bisa dimaklumi, ini akibat desain yang kurang cocok dan implementasi yang amburadul. Sebagai contoh, saat ini terasa sangat tabu bagi seorang siswa mengalami tinggal kelas. Padahal dulu tinggal kelas adalah sebuah hal yang normal saat siswa belum mampu memenuhi target akademis minimal. Kurikulum Merdeka tidak secara eksplisit melarang siswa tinggal kelas. Namun keputusan siswa tinggal kelas akan memberikan beban yang lebih besar kepada guru, sebagai contoh kalau siswa belum bisa berhitung maka guru dituntut untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat bagi siswa agar siswa tersebut dapat mengejar ketertinggalannya. Sebenarnya maksudnya baik karena memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki diri namun realitas di lapangan dengan banyaknya jumlah siswa yang harus mendapatkan pengayaan dan beban pekerjaan guru misalnya dalam hal administrasi yang terlalu banyak membuat hal ini sulit untuk difasilitasi. Kemudian di level pejabat dinas adanya anomali siswa yang belum kompeten ini dianggap sebagai aib. Adanya data siswa yang belum mampu secara akademik ini seringkali dianggap sebagai noda atau dosa statistik, akibatnya bisa ditebak demi mengejar statistik siswa 100% memenuhi ketuntasan minimal akhirnya semua diizinkan naik kelas.
Terbaru, ada isu yang masih hangat yaitu mengenai nilai rata-rata Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025 yang mengundang keprihatinan, bagaimana tidak di mata pelajaran Matematika nilai rata-rata nasionalnya hanya di kisaran 34, ini juga dialami oleh mata pelajaran IPA lainnya. Dari penelurusan saya, ada permasalahan teknis yang dihadapi siswa ketika mengerjakan TKA yang terkait dengan sarana prasarana. Ada pula kritik yang disampaikan mengenai kualitas soal yaitu bobot soal yang memang sulit dengan durasi waktu yang singkat, demikian pula ada materi soal yang diklaim belum pernah diajarkan di kelas. Dalam perspektif saya, TKA 2025 ini adalah bentuk ketidaksinkronan antara kurikulum yang berjalan dengan model evaluasi yang dipilih. Selama 10 tahun ke belakang dunia pendidikan, khususnya di sekolah menengah, dibawa ke pendekatan "santai" ala negara nordik sementara soal TKA 2025 ini bisa dibilang adalah model evaluasi ala negara Asia Timur yang kompetitif dan menuntut latihan drill soal terus menerus. Jadi haruslah konsisten kalau memilih pendekatan ala negara Nordik tipe evaluasinya harus disesuaikan. Tapi kalau memang mau ujiannya ala negara Asia Timur, seharusnya kurikulumnya dirancang lebih "kejam" dan kompetitif.
2. Mahalnya Biaya Pendidikan Tinggi
Puluhan tahun lalu, menempuh pendidikan tinggi di universitas adalah salah satu cara untuk "naik kelas" secara sosial. Anak seorang petani misalnya sangat berpeluang untuk melanjutkan pendidikan di UI atau UGM, beasiswa tersedia dan SPP pada waktu itu dirasa masih masuk akal. Namun masuk di era PTNBH dan UKT, biaya pendidikan di universitas terasa naik drastis. Memang ada perbedaan, dulu sebelum era UKT ada biaya SKS yang harus dibayarkan mahasiswa. Namun saat ini keberadaan UKT yang dimaksudkan untuk menyederhanakan komponen biaya universitas (cukup 1 komponen biaya yang dibayar) nampaknya telah bergeser dari tujuan awalnya, hal ini ditandai dengan adanya biaya SPI yang ditarik oleh sejumlah perguruan tinggi. Status PTNBH yang semakin banyak disandang sejumlah PTN juga seolah menjadi justifikasi untuk menaikkan biaya.

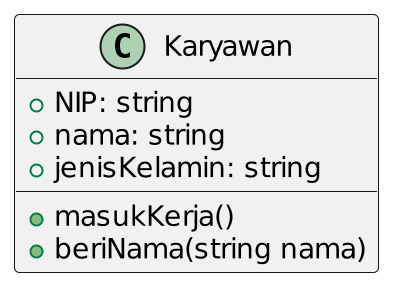

Comments
Post a Comment